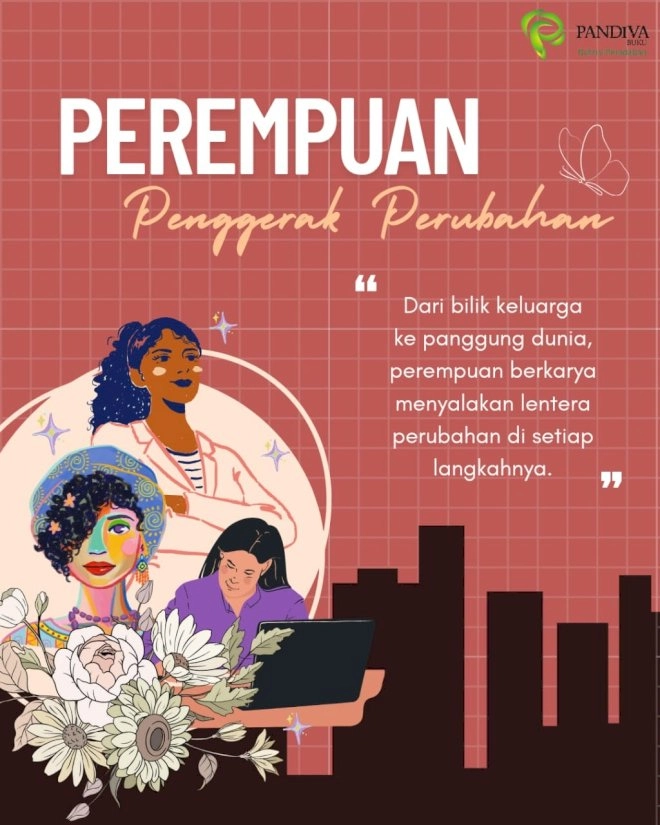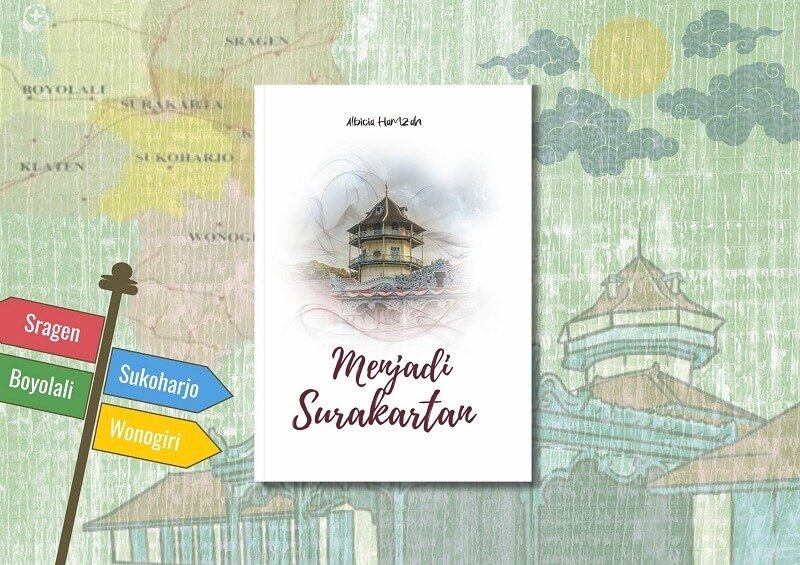
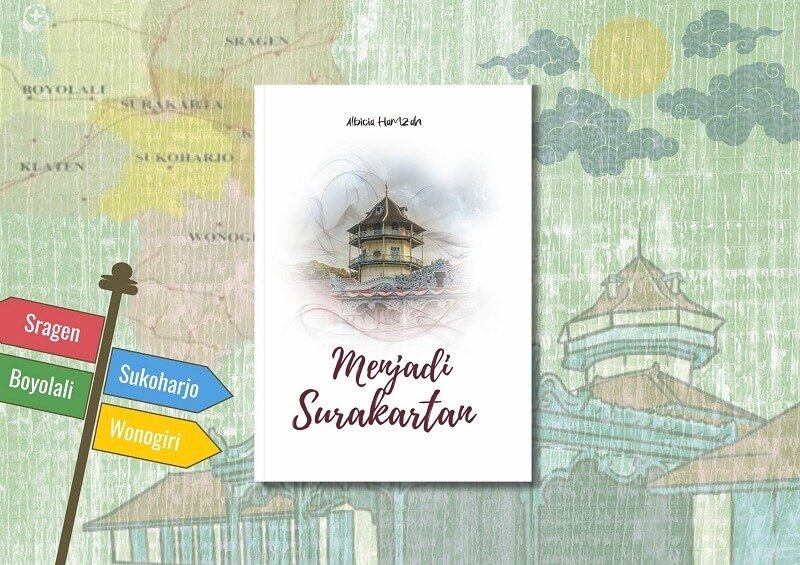
Menyulam Satu Surakartan
/ Literatur
Menjadi Surakartan adalah ‘menjadi Indonesia’ berbekal keberanian menata masa depan.
Pembangunan sebuah kawasan tidak pernah terlepas dari kesadaran atas sejarah dan identitas bersama. Di wilayah eks-Karesidenan Surakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Subosukawonosraten atau akronim dari Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, dan Klaten, kesadaran itu menjadi kunci perumusan arah dan pola pembangunan lintas daerah yang saling terhubung.
Buku Menjadi Surakartan yang ditulis oleh Albicia Hamzah hadir sebagai refleksi dan tawaran gagasan untuk membingkai semangat pembangunan kawasan yang sekian lama terikat oleh kedekatan geografis, sosiologis, dan historis tersebut.
Alih-alih sekadar menghimpun potensi lokal, buku ini berusaha mengajak pembaca untuk melihat Subosukawonosraten sebagai satu kesatuan strategis. Sejarah panjang yang menyatukan ketujuh daerah tersebut semestinya menjadi landasan kuat untuk membangun masa depan bersama, bukan dengan penyeragaman, melainkan dengan mempertemukan kekuatan masing-masing.
Buku Menjadi Surakartan yang terbit pada 2023 disusun dalam tiga bagian utama, yakni kepemimpinan dan pranata lokal, potensi sosial-ekonomi daerah, serta strategi kolaboratif dalam pengembangan kawasan. Penulis menyampaikan gagasan-gagasan tersebut melalui esai-esai bernas yang ditulis dengan gaya reflektif.
Bagian pertama membahas pentingnya kepemimpinan lokal yang berpijak pada nilai dan karakter masyarakat. Dalam tulisan ‘Kepemimpinan Surakartan’ dan ‘Merindu Pemimpin Berbudaya’, penulis menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tak hanya bergantung pada sumber daya atau infrastruktur, tetapi juga pada kehadiran sosok pemimpin yang memiliki empati serta pemahaman mendalam terhadap pranata sosial di wilayahnya.
Di samping itu, penulis menggarisbawahi peran generasi muda dalam mengisi ruang-ruang kepemimpinan, terutama mereka yang tumbuh dengan wawasan global, namun terikat dengan identitas lokalnya.
Nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Surakartan dilihat sebagai kekuatan kultural yang bisa dikembangkan menjadi fondasi pembangunan. Dalam hal ini, penulis mendorong kembali ke pranata lokal yang telah teruji sebagai penopang harmoni sosial ketimbang pembangunan di atas struktur baru yang asing.
Mengapa penting? Mengingat kekosongan nilai kerap menjadi kendala dalam kebijakan yang baik secara teknis, namun dalam realitasnya di masyarakat justru tidak membumi.
Selanjutnya, bagian kedua menyajikan eksplorasi potensi dari masing-masing kabupaten di kawasan Surakartan. Penulis membingkai setiap daerah sebagai simpul kekuatan yang saling melengkapi. Karanganyar dengan sektor pariwisata spiritual dan sejarahnya, Sragen dengan kawasan purbanya, Boyolali dengan sektor peternakannya, Wonogiri dengan karakter sosial perantaunya, hingga Sukoharjo dengan dinamika ketenagakerjaan.
Semua isu ditulis bukan untuk menonjolkan superioritas masing-masing, tetapi demi memperlihatkan kekuatan kawasan yang terletak pada rajutan keragaman berikut semangat kolaborasi.
Tulisan berjudul ‘Sinergi Pariwisata Karanganyar’, ‘Kawasan Purba dan Peluang Pariwisata Sragen’, hingga ‘Potensi dan Partisipasi Tenaga Kerja Sukoharjo’, di antaranya, menunjukkan bahwa pembangunan bisa diarahkan menjadi lintas batas administratif ketika ada kesepahaman visi dan koordinasi antarwilayah. Penulis pun menyoroti pentingnya keterlibatan komunitas lokal sebagai aktor utama, bukan sekadar objek pembangunan.
Sementara itu, bagian ketiga menampilkan strategi-strategi konkret untuk memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan Surakartan. Penulis memberikan contoh-contoh aplikatif, misalnya pemanfaatan e-commerce oleh peternak susu segar Boyolali, pengembangan ekonomi kreatif, hingga peluang kolaborasi antara organisasi profesi dan pemerintah daerah.
Penekanan pada pendekatan digital dan kolaboratif berarti kawasan ini memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, selama ekosistem pendukungnya dibentuk secara serius.
Tulisan-tulisan pada bagian akhir buku memperluas cakupan tema, di antaranya bagaimana lembaga berbasis nilai seperti pesantren dan komunitas keagamaan turut berperan dalam memperkuat ketahanan sosial.
Gerakan Sosial
Semua gagasan tersebut tidak hadir secara menggurui, tetapi tersaji dengan narasi yang disusun penuh empati beserta kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat lokal. Penulis mengajak pembaca untuk melihat pembangunan sebagai proses birokratis, juga memahaminya sebagai gerakan sosial.
Menjadi Surakartan ditulis dengan gaya bahasa yang mengalir, namun padat makna. Gagasan-gagasan yang ditawarkan bersandar pada kenyataan lokal yang ada. Tuturnya tidak kaku, sehingga dapat dikembangkan percakapan-percakapan baru tentang pembangunan kawasan berbasis identitas.
Bagi pembaca yang berkecimpung dalam bidang kebijakan publik, pengembangan wilayah, atau kerja-kerja kolaboratif lintas kabupaten, baik itu kepala daerah maupun akademisi, buku setebal 132 halaman ini menyajikan banyak ide yang dapat diadaptasi, terutama bagaimana menata ulang hubungan antarwilayah yang lebih visioner.
Sementara bagi masyarakat umum, Menjadi Surakartan adalah panggilan untuk kembali mengenali jati diri dan ambil bagian dalam upaya membangun masa depan bersama.
Di tengah tekanan global dan disrupsi sosial-ekonomi, masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menyulam kekuatan lokal menjadi jaringan kolektif yang kokoh. Hal inilah yang berusaha disuarakan oleh buku Menjadi Surakatan.
Bahwa kunci dari pembangunan nasional bukan terletak di pusat, tetapi di daerah-daerah yang mampu bekerja sama dan saling mendukung. Menjadi Surakartan adalah ‘menjadi Indonesia’ dengan keberanian untuk menata masa depan bersama.
Editor: Rahma Frida