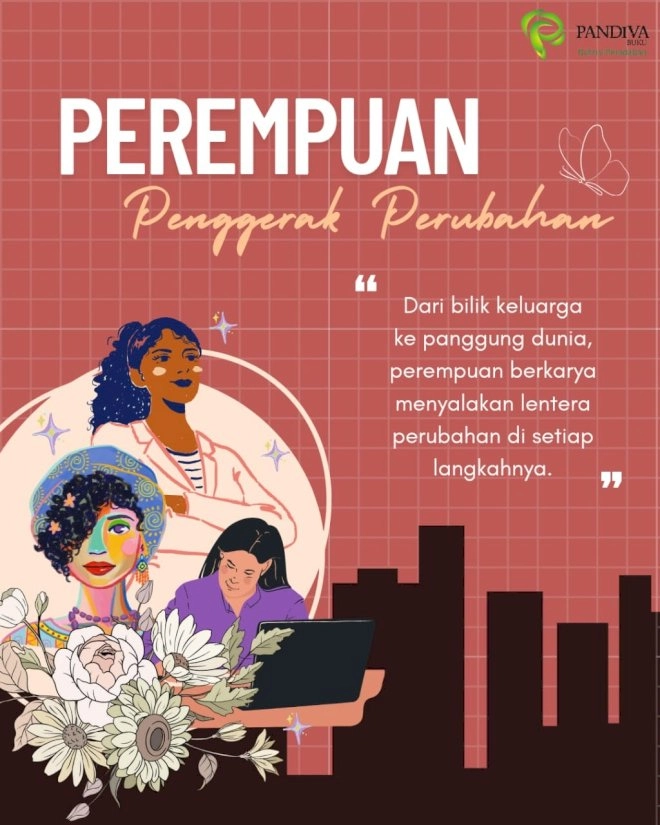Memahami Aksi Massa
/ Literatur
Aksi massa bukan hanya perilaku kolektif atau akibat logis dari mekanisme-mekanisme struktural.
Bagus Sigit Setiawan
Direktur Program Masjid Raya Sheikh Zayed. Alumnus Fakultas Hukum UMS.
Penulis buku Santri Surakartan. Tinggal di Kartasura.
Sejak lama, fenomena kekerasan massa seperti kerusuhan, huru-hara, pengeroyokan, penjarahan, pembantaian, pemberontakan, revolusi, dan seterusnya menjadi fenomena yang begitu diminati, tidak hanya oleh para politikus, melainkan juga sejarawan, sosiolog, filsuf, psikolog, sastrawan, dan kritikus kebudayaan. Tentu dengan latar belakang minat masing-masing.
Dalam kekerasan massa, kerumitan peristiwa dan dinamika destruksinya lebih menyerupai sebuah malapetaka daripada hasil perbuatan tangan manusia yang membangkitkan rasa ngeri dalam diri manusia. Hubungan sosial yang dalam hidup sehari-hari relatif tertata baik, tidak lagi berfungsi.
Individu-individu kehilangan distansi satu sama lain, membanjiri jalan-jalan dan tidak lagi bertingkah laku sebagaimana lazimnya. Guru Besar Filsafat Universitas Pelita Harapan Jakarta, Budi Hardiman, menyebut mereka seakan-akan telah menjelma menjadi ‘monster berkepala banyak’.
Kekerasan kolektif sering meletus dalam sejarah manusia. Pemberontakan budak di zaman Romawi kuno, para petani di Jerman pada akhir Abad Pertengahan atau di Banten pada awal abad ke-20, atau revolusi-revolusi besar di zaman modern.
Selain itu, ada tragedi Priok, kerusuhan di Ambon dan Sampit, Kuda Tuli, kekerasan yang menyasar etnis Tionghoa pada Mei 98, aksi pengemudi-pengemudi ojek online atas nama solidaritas seprofesi, dan yang terakhir, bentrokan di Pemalang Jawa Tengah antara kelompok anti-habib dan pro-habib. Semua ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sejarah panjang terkait kekerasan massa atau ‘tradisi’ kekerasan massa.
Apa Itu ‘Massa’?
Seorang sosiolog asal Jerman, Veit-Michael Bader, membuka wacana tentang kekerasan massa. Bader berusaha menyusun teori tindakan tentang massa yang menyebut bahwa kekerasan massa berasal dari tangan manusia, namun dinamika peristiwa ini dapat melampaui intensi-intensi para pelakunya. Seperti halnya chaos bukanlah ledakan spontan ressentiment, melainkan dipersiapkan melalui proses-proses tindakan manusia. Chaos adalah bagian dari suatu proyek pengubah sebuah tatanan yang dianggap tidak adil.
Ada banyak pengertian tentang massa yang kerap dimengerti hanya mengacu kepada berbagai fenomena, atau sesuatu yang terkait dengan kuantitas; mengacu pada jumlah yang sangat besar, konsentrasi manusia-manusia pada suatu tempat dan konsentrasi itu tidak lama bertahan. Misalnya, kerumunan di pasar, pusat perbelanjaan, para jamaah haji di Makkah, para peziarah di Vatikan, serta pengunjung konser musik dan sholawatan.
Sebagian merujuk pengertian lain bahwa massa tidak mengacu pada kegiatan-kegiatan kumpulan manusia yang masih dalam bingkai institusional, sebagaimana beberapa contoh tadi, melainkan mengacu pada aksi-aksi kumpulan manusia yang melampau batas-batas institusional. Inilah yang disebut ‘massa’.
Sekumpulan manusia menjadi ‘massa’ jika mereka bertindak dengan mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku dalam situasi sehari-hari. Selalu berkaitan dengan situasi khusus, dengan keadaan sosial yang abnormal.
Dalam pengertian ini, kumpulan orang dalam demonstrasi damai, istighosah, perayaan ulang tahun partai, dan tablig akbar bukanlah ‘massa’, karena dilakukan dalam bingkai hukum dan situasi normal sehari-hari. Penonton konser musik dan wayang, serta kerumunan penikmat sound horeg yang ramai dibicarakan belakangan, termasuk dalam bingkai tersebut, yaitu bukan ‘massa’. Namun demikian, kumpulan itu akan berubah menjadi ‘massa’ manakala mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu, jahat, merusak, serta mengabaikan norma-norma sosial.
Mengapa harus ditarik pengertian demikian, tentu sebagai cara kita untuk memilah antara kerumunan manusia yang sesuai dengan norma-norma sosial dan kerumunan yang mengabaikan norma-norma sosial. Gampangnya, dapat untuk membedakan, mana rombongan walikota dan mana rombongan bromocorah.
Aksi Massa
Budi Hardiman menyebut ‘aksi massa’ yang mengingatkan kita akan tornado atau letusan gunung berapi yang sekonyong-koyong memorak-porandakan sebuah kota atau mengacau-balaukan seluruh bangsa.
Beberapa orang yakin, peristiwa kekerasan massa mempercepat kelahiran sebuah tatanan politis yang baru dan menganggapnya sebagai tonggak Sejarah. Namun, bagi semua orang yang mengalaminya, peristiwa tersebut jelas merupakan kekacauan, sebuah situasi yang melumpuhkan nalar mereka.
Pengalaman kacau ini yang disinggung Rocky Gerung tempo hari pada saat diundang sebuah televisi bertema Palestina. Sayang, tidak ada yang menanggapinya. Bisa jadi, banyak yang tidak paham. Kemarin, Rocky menyebut nama Hannah Arendt.
Gustave Le Bon, Bapak Psikologi Massa, dalam Psychologie des Foules seperti dikutip oleh Hardiman, menulis bahwa ‘massa itu bodoh, mudah diprovokasi, bersifat rasistis’, atau singkatnya irasional.
‘Massa’ dalam bayangan Le Bon adalah mereka yang senantiasa terkungkung dalam batas-batas ketidaksadaran, tunduk pada segala pengaruh, mudah diombang-ambingkan oleh emosi dan mudah percaya. Di dalam ‘massa’, individu-individu yang berbeda-beda memiliki ‘dorongan-dorongan, nafsu-nafsu dan perasaan-perasaan yang sangat mirip dan bertingkah laku sama.
Sikap melecehkan massa semacam itu dapat kita temukan juga pada Sigmund Freud dan Ortega Y. Gasset, dua murid Le Bon yang tidak banyak mengubah tesis-tesis dasar gurunya. Situasi massa adalah ‘regresi ke aktivitas psikis yang primitif…. Bangkitnya kembali gerombolan purba dalam diri kita’, demikian terang Freud. Gasset lalu menyambung bahwa ‘massa bertindak hanya dengan satu cara: mengeroyok’.
Tesis tentang irasionalitas massa tidak hanya mewarnai literatur sejak Le Bon, melainkan juga pemahaman kita sehari-hari. Seperti penggunaan istilah mob dan gerombolan yang sering dipakai dan bermuatan penilaian negatif.
Gerhard Colm menyebutnya stimmung sgemeinschaft yaitu komunitas yang berindak menurut perasaan. Colm memahami bahwa massa adalah sebuah kelompok yang tindakan-tindakan dan pencapaian tujuannya hanya dapat terwujud melalui perasaan-perasaan yang sama.
Hardiman menyebut pendirian Le Bon dan para pengikutnya ini, pendirian mentalistis, berhadap-hadapan dengan pendirian strukturalistis tentang massa yang dianut oleh teori-teori Marxis. Pendekatan Marxis mencari alasan dan kondisi terbentuknya massa tidak pada sisi subyektif atau proses-proses mental individu, melainkan pada sisi obyektif masyarakat, yakni pada proses-proses perubahan sosial dan perkembangan negara nasional. Teori-teori Marxis menemukan peran emansipatoris massa atau tepatnya ‘massa yang sadar-kelas’.
Mereka tidak memandang fenomena massa sebagai ledakan emosi atau pelampiasan naluri-naluri biadab, karena aksi massa yang revolusioner berasal dari konflik kepentingan kelas-kelas atau dari ketidaksamaan struktural. Dalam kerumunan seperti ini, para peserta aksi massa tidak bertindak melulu karena emosi, melainkan ‘strategis’. Mereka mengikuti kepentingan-kepentingan kelas mereka yang bersifat objektif.
Dengan kata lain, aksi massa bersifat rasional. Dalam arti ini, massa adalah akibat yang niscaya dari perkembangan sejarah dan kontradiksi-kontradiksi struktural. Teori-teori tentang massa sampai kini tidak bergerak melampaui kedua pendirian tersebut. Pendirian yang satu mereduksi massa pada afeksi belaka, dan yang lain pada kalkulasi strategis murni.
Tindakan Kolektif
Namun, Veit-Michael Bader menawarkan teori lain, yaitu teori Tindakan Kolektif yang tidak reduksionis untuk menerangkan massa secara memadai. Teori yang memperhitungkan multidimensionalitas peristiwa aksi massa dan tidak mereduksi begitu saja pada afeksi irasional atau kalkulasi rasional, kebebasan murni atau keniscayaan belaka, mentalitas atau struktural, dan seterusnya.
Solusi yang diajukan Teori Tindakan Kolektif atas dilema afeksi atau kalkulasi adalah pemahaman yang tepat mengenai tindakan manusia. Manusia yang ikut serta dalam aksi-aksi massa tidak melulu digerakkan oleh kemarahan, frustrasi, agresi, kebencian, atau ketidakpuasan, seperti binatang buas yang lapar. Mereka juga tidak murni mengikuti orientasi strategis yang melekat pada kepentingan-kepentingan mereka. Aksi massa bukan hanya ‘perilaku kolektif’, juga bukan ‘akibat logis’ dari mekanisme-mekanisme struktural.
Teori Tindakan Kolektif mendekati aksi massa sebagai suatu ‘tindakan’. Di sini perilaku dibedakan secara tegas dari tindakan. Perilaku berkenaan dengan spontanitas naluriah, sementara tindakan menyangkut kesadaran manusiawi.
Biasanya, seseorang bertindak secara individual dalam rangka sistem-sistem norma yang dipatuhi bersama. Dalam keadaan-keadaan tertentu, orang berkumpul dan bertindak bersama di luar kerangka institusional itu untuk mengubah sesuatu yang secara individual tidak dapat dilakukan. Tindakan yang dilakukan bersama-sama inilah yang kita sebut ‘tindakan kolektif’.
Teori Bader ini saya rasa lebih dekat dengan banyak ajaran yang tumbuh di dalam lingkungan penghayat keyakinan, pemeluk agama, serta alam tradisi dan kebudayaan Indonesia. Tindakan kolektif mirip dengan maksud dari peribahasa kita, ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’. Tindakan kolektif adalah kesadaran manusiawi untuk ber-‘gotong royong’, sebagai kunci perjuangan massa.
Editor: Arif Giyanto