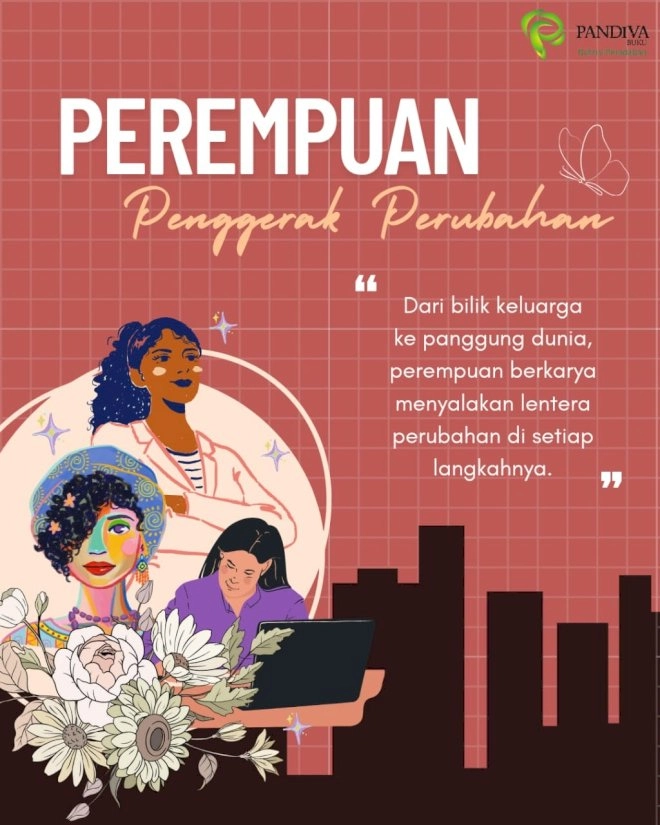Krisis Human Capital Lulusan Perguruan Tinggi
/ Opini
Kuliah yang tak membentuk kemampuan adaptif dapat berbuah lahirnya generasi sarjana yang kehilangan daya guna dan daya harap.
M. Farid Wajdi
Guru Besar Ilmu Manajemen UMS
Direktur Pascasarjana UMS
Fenomena baru sedang melanda China. Media lokal menyebutnya sebagai ‘anak dengan ekor busuk’. Sebuah sebutan bagi para sarjana muda yang gagal mendapatkan pekerjaan sesuai bidang studinya, bergaji rendah, dan akhirnya bergantung pada dukungan orang tua.
Istilah ini diambil dari perumpamaan ‘gedung ekor busuk’, yaitu proyek perumahan yang mangkrak dan menjadi beban ekonomi. Kini, ‘gedung’ itu menjelma menjadi generasi muda terdidik yang kehilangan nilai tambah dari pendidikan tinggi.
Kasus tersebut menjadi simbol krisis human capital; ketika pendidikan tinggi tidak lagi mampu menghasilkan tenaga kerja yang relevan dan produktif. Berdasarkan data pemerintah China, jumlah lulusan universitas tahun 2025 mencapai 12,22 juta orang, naik dari 9 juta pada 2021. Namun, jutaan di antaranya masih menganggur atau bekerja di sektor rendah upah.
Kondisi pendidikan tanpa nilai ekonomi itu dapat dijelaskan melalui teori human capital yang dikembangkan oleh Gary S. Becker dan Theodore W. Schultz. Keduanya berpandangan bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja merupakan bentuk investasi modal manusia yang akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, teori ini memiliki syarat penting. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan ekonomi dan mampu membentuk kemampuan adaptif manusia terhadap perubahan.
Masalah di China muncul karena keseimbangan yang tidak terjaga. Di satu sisi, pendidikan tinggi memproduksi jutaan sarjana dari berbagai bidang, mulai dari desain, teknik kimia, hingga vokasi makanan dan obat. Namun di sisi lain, pasar tenaga kerja justru beralih ke sektor manufaktur digital, otomasi, dan kecerdasan buatan (AI).
Dengan kata lain, investasi pendidikan tidak menghasilkan return ekonomi yang diharapkan. Lulusan yang tidak terserap sesuai bidangnya terjebak dalam pekerjaan sementara dengan gaji rendah. Mereka menjadi cerminan overeducated but underemployed generation.
Dari perspektif Becker, inilah bentuk kegagalan konversi modal manusia menjadi produktivitas ekonomi. Sementara menurut Schultz, krisis ini juga menandakan kegagalan sistem pendidikan dalam membentuk kemampuan adaptif (adaptive capacity), yaitu kecakapan untuk menyesuaikan diri terhadap transformasi teknologi dan struktur industri yang berubah cepat.
Fenomena ‘anak dengan ekor busuk’ bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga krisis psikologis generasi muda. Banyak lulusan kehilangan rasa percaya diri, merasa sia-sia, dan memilih mundur dari persaingan kerja, yang dikenal dengan istilah tangping atau ‘merunduk’.
Mereka bukan tidak ingin bekerja, tetapi merasa model karier tradisional sudah tidak menjanjikan. Fenomena ini menimbulkan efek domino menurunnya motivasi belajar, hilangnya martabat profesional, dan meluasnya pesimisme sosial terhadap nilai pendidikan tinggi.
Tak Sekadar Gelar
Kondisi di China seharusnya menjadi peringatan dini bagi Indonesia. Kita juga tengah mengalami lonjakan lulusan perguruan tinggi setiap tahun, sedangkan daya serap dunia kerja belum cukup kuat. Bila sistem pendidikan tidak segera diselaraskan dengan kebutuhan industri dan teknologi, fenomena serupa bisa terjadi di Tanah Air.
Dari pandangan teori human capital Becker-Schultz, terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, pendidikan harus berbasis kebutuhan ekonomi nyata. Kurikulum perguruan tinggi perlu disusun berdasarkan peta industri dan kebutuhan daerah, bukan semata mengejar jumlah lulusan, dan cepatnya masa perkuliahan.
Kedua, keterampilan adaptif lebih penting daripada hafalan akademik. Dunia kerja modern membutuhkan lulusan yang tangguh, mampu belajar ulang (reskilling), dan menyesuaikan diri dengan teknologi baru.
Ketiga, kolaborasi universitas dan industri harus diperkuat. Program magang, kerja praktek, riset terapan, dan pengembangan vokasi akan membantu menjembatani jarak antara kampus dan pasar kerja.
Keempat, mendorong kewirausahaan muda. Pendidikan tidak boleh hanya mencetak pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja yang inovatif dan mandiri (employability skill).
China adalah contoh negara yang berhasil membangun infrastruktur fisik, tetapi kini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan infrastruktur manusia. Teori Becker dan Schultz mengingatkan bahwa investasi terbesar sebuah bangsa adalah pada manusianya sendiri. Namun, investasi itu hanya akan berharga jika menghasilkan produktivitas nyata yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Bagi Indonesia, saatnya memperkuat arah pendidikan agar tidak sekadar mencetak gelar, melainkan membangun kapasitas manusia yang kompeten, terampil, fleksibel, produktif, dan adaptif. Tanpa perubahan strategi pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan, kita bisa menghadapi petaka serupa di China, yakni lahirnya generasi sarjana yang kehilangan daya guna dan daya harap.
Editor: Astama Izqi Winata