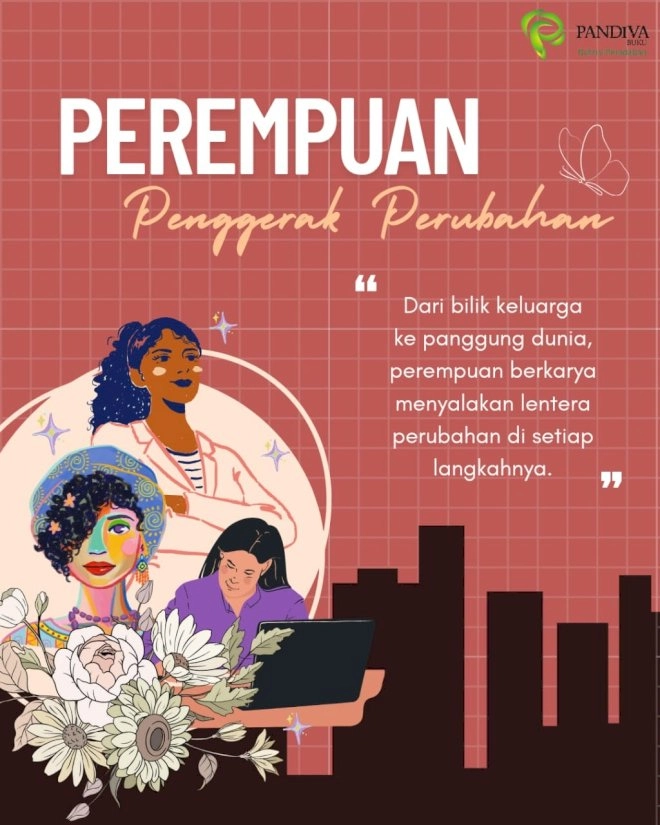Centang Perenang Kebijakan Ketahanan Pangan
/ Opini
Ketahanan pangan mustahil terpenuhi tanpa swasembada dan hilirisasi.
Anton A. Setyawan
Guru Besar Ilmu Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta
Penciptaan ketahanan pangan bagi Indonesia menjadi salah satu target pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Target ini relevan dengan permasalahan umum yang akan dihadapi berbagai negara di masa depan, yaitu kelangkaan pangan, air, dan energi sebagai akibat perubahan iklim.
Sebagai negara beriklim tropis dengan berbagai variasi vegetasi pangan, Indonesia seharusnya mampu mencapai swasembada pangan seperti dekade 1980-an semasa rezim Orde Baru. Swasembada pangan, khususnya beras, di masa Orde Baru menjadi prestasi yang sulit diulangi. Pada masa itu, pemerintah dengan berbagai upaya berusaha memperkuat sektor primer, terutama pertanian pangan, sehingga pasokan beras di Indonesia mampu memenuhi permintaan dalam negeri.
Orde Baru berupaya memperbaiki sektor pertanian dengan kebijakan lahan serta pola ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian. Selain itu, menciptakan bibit padi unggul, juga memberikan subsidi pupuk dan melakukan pengendalian hama. Perbaikan dari sisi produksi pertanian dilakukan dengan komprehensif.
Pemerintah Orde Baru membangun kelembagaan ekonomi pertanian dan menjaga stabilitas harga. Lembaga yang menjaga pasokan dan harga komoditas pangan di masa Orde Baru bernama Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebuah lembaga pemerintah dengan anggaran yang besar untuk menjaga harga komoditas pangan.
Ketika Orde Baru berkuasa, Bulog membeli sebagian besar hasil panen, apabila ada panen raya dengan harga yang ditentukan pemerintah. Harga tersebut berada pada level yang menguntungkan petani berdasarkan biaya produksi yang mereka keluarkan. Pada saat paceklik, Bulog memasok beras ke pasar sehingga tidak terjadai kenaikan harga secara drastis.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam menjaga stabilitas harga sehingga tetap menguntungkan bagi petani tetapi juga tidak menyebabkan konsumen membayar mahal untuk harga beras disebut dengan administered price atau harga yang diatur mekanismenya oleh pemerintah.
Pemerintah menetapkan harga batas atas atau batas bawah sesuai dengan kebutuhan untuk mengendalikan harga. Kebijakan ini sangat mahal karena kebutuhan anggaran untuk membeli gabah di pasar apabila sedang musim panen raya sangatlah besar. Hal ini dikarenakan harga versi pemerintah bisa jadi di atas harga pasar.
Dalam konteks dan kebijakan seperti itulah Indonesia kemudian berhasil menikmati swasembada pangan pada dekade 1980-an, hingga perubahan besar pun datang, ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998. Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia pun harus mengikuti saran International Monetary Fund (IMF) sebagai konsekuensi pinjaman Indonesia pada lembaga tersebut untuk membiayai dampak krisis ekonomi.
Di mata IMF, Bulog dianggap sebagai lembaga yang memonopoli perdagangan bahan pokok sehingga berlawanan dengan mekanisme pasar. Oleh karena itu, lembaga ini harus dikurangi wewenangnya. Pasca keputusan tersebut, bermulalah era pelemahan sektor pertanian pangan di Indonesia.
Swasembada Dahulu Hilirisasi Kemudian
Kamis (21/11/2024), Bank Indonesia Kota Surakarta bekerja sama dengan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Solo serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (FEB UMS) menyelenggarakan seminar tentang hilirisasi pangan di Auditorium Mohamad Djazman.
Dalam diskusi disinggung tentang hilirisasi pangan yang tidak dapat dilepaskan dari produktivitas tanaman pangan. Berdasarkan data dari Indikator Pertanian tahun 2023 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks produktivitas tanaman pangan Indonesia menunjukkan angka yang fluktuatif.
Pada tahun 2019, indeks produksi tanaman pangan mencapai 94,42. Angka ini turun menjadi 77,22 pada tahun 2020. Setahun berikutnya, tahun 2021, turun tipis menjadi 77,10. Sementara tahun 2022, naik drastis menjadi 80,86. Pada tahun 2023, turun kembali menjadi 78,25.
Selanjutnya, hilirisasi pangan sebenarnya merupakan fase lanjutan dari swasembada pangan. Artinya, mustahil hilirisasi pangan dapat diwujudkan tanpa swasembada pangan. Swasembada pangan di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Hal ini bisa dilihat dari data impor hasil tanaman pangan di Indonesia tahun 2022 dan 2023.
Pada tahun 2022, Indonesia mengimpor 418.776,967 ton, lalu tahun 2023 angka ini meningkat menjadi 3.048.774,07 ton. Tahun 2022 impor jagung mencapai 277.137,541 ton, dan pada tahun 2023 turun menjadi 8.792,601 ton. Impor kacang hijau pada tahun 2022 mencapai 98.149,538 ton, kemudian tahun 2023 naik menjadi 117.756,715 ton.
Tiga komoditas pangan penting di Indonesia ini menunjukkan bahwa negara masih memiliki ketergantungan impor yang tinggi dalam menjaga harga masing-masing komoditas tersebut. Kebijakan impor komoditas pangan juga menunjukkan kelemahan dalam produksi serta tata kelola perdagangan komoditas pangan.
Ketika sektor pertanian pangan gagal mengantisipasi fluktuasi pasokan dan permintaan komoditas pangan, muncullah persoalan kenaikan harga komoditas pangan saat paceklik atau gagal panen, lalu diatasi dengan impor. Pada sisi lain, saat panen raya, harga komoditas pangan justru mengalami penurunan sehingga petani rugi besar. Struktur pasar komoditas pangan seperti itu menunjukkan adanya otoritas para ‘oligopolis’ yang mampu menentukan harga dan jumlah pasokan di pasar.
Manajemen rantai pasok komoditas pangan menunjukkan adanya masalah dari sisi informasi dan kelembagaan. Tidak ada lagi lembaga seperti Bulog pada zaman Orde Baru yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan harga komoditas pangan strategis. Beberapa kali terjadi, harga komoditas pangan seperti daging ayam potong mengalami penurunan dan merugikan petani. Mereka pun membagi-bagikan ayam pada masyarakat secara gratis.
Gangguan pasokan terkadang terjadi tanpa diketahui petani atau peternak. Contohnya, belakangan peternak sapi di Boyolali ramai-ramai membuang susu, karena pabrik pengolahan susu tidak menerima setoran susu dari peternak tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, ratusan liter susu sapi mentah dibuang percuma.
Industri Pangan Berbasis UMKM
Langkah strategis lain dalam perumusan kebijakan hilirisasi pangan yakni mempersiapkan industrinya. Setelah swasembada pangan tercapai, komoditas pangan harus masuk dalam proses peningkatan nilai tambah menjadi produk jadi. Hilirisasi pangan sudah seharusnya diwujudkan dalam bentuk industri pangan yang kuat.
Industri pangan memerlukan dukungan kebijakan industri tersendiri dari pemerintah, karena sebagian besar pelaku bisnisnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka memerlukan dukungan pemerintah dari aspek teknologi produksi, akses permodalan, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Industri pangan juga membutuhkan inovasi, dari produksi hingga pemasaran. Para pelaku bisnis UMKM pangan sebenarnya mempunyai banyak inovasi produk. Sebagai contoh, komoditas cabai, tomat, dan bawang merah telah menjadi bahan baku industri pangan. Ada pula peternak ikan nila dan lele yang mengembangkan hilirisasi pangan menjadi tepung ikan, bakso ikan, dan abon ikan.
Dukungan kebijakan pemerintah tersebut untuk memastikan daya saing industri pangan Indonesia yang kuat. Dalam jangka panjang, industri pangan sebagai hilir dari pertanian pangan di Indonesia dapat diarahkan menjadi industri orientasi ekspor dan substitusi impor.
Editor: Rahma Frida